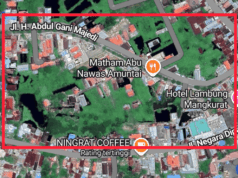CakrawalaiNews.com — Media sosial di Indonesia kian menjelma menjadi pengadilan jalanan digital. Setiap persoalan pribadi, utang-piutang, konflik bisnis, hingga dugaan penipuan, dengan mudah diadili di ruang publik tanpa proses, tanpa bukti yang diuji, dan tanpa hak jawab yang setara.
Nama dipampang. Foto disebar. Narasi dibangun sepihak. Vonis dijatuhkan ramai-ramai.
Ironisnya, semua itu dilakukan di negara hukum.
Dari Emosi ke Eksekusi Sosial
Dalihnya nyaris seragam: “Sekadar mengingatkan”, “biar orang lain tidak jadi korban”, atau “sudah tidak ada jalan lain”. Namun di balik dalih itu, yang terjadi sesungguhnya adalah eksekusi sosial berbasis emosi, bukan pencarian keadilan.
Seseorang yang “diduga” bermasalah langsung dicabut hak dasarnya sebagai warga negara. Reputasi dihancurkan. Tekanan sosial dilipatgandakan. Bahkan keluarga ikut terseret. Semua dilakukan tanpa putusan pengadilan.
Di titik ini, media sosial tak lagi menjadi ruang ekspresi, melainkan alat penghukuman massal.
UU ITE Bukan Ornamen
Harus ditegaskan: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bukan sekadar teks hukum tanpa daya. Menyebarkan tuduhan, apalagi dengan identitas jelas, berpotensi memenuhi unsur pencemaran nama baik dan fitnah, sekalipun disertai kata “diduga”.
Kata “diduga” bukan tameng hukum. Ketika narasi yang dibangun menggiring opini publik untuk menghakimi, maka unsur pelanggaran tetap terbuka lebar.
Banyak warganet keliru memahami kebebasan berekspresi sebagai kebebasan menuduh. Padahal, kebebasan berekspresi berhenti ketika hak orang lain dilanggar.
Admin Grup Bukan Penonton
Yang lebih memprihatinkan, praktik ini dilegitimasi oleh grup-grup media sosial yang tumbuh tanpa etika pengelolaan. Unggahan bermuatan tuduhan lolos begitu saja.
Admin memilih aman dengan kalimat klise: “Postingan di luar tanggung jawab admin.”
Sikap ini bukan netral. Ia permisif.
Dalam ekosistem digital, membiarkan konten bermasalah berarti ikut memperluas dampaknya. Grup bukan ruang privat. Ia adalah ruang publik digital yang punya konsekuensi hukum dan sosial.
Viralitas Mengalahkan Keadilan
Masalah terbesar dari pengadilan medsos adalah satu hal: viralitas mengalahkan kebenaran. Yang paling keras bersuara dianggap paling benar. Yang paling cepat menyebar dianggap paling sah.
Akibatnya, hukum terdesak oleh opini. Proses digantikan tekanan. Klarifikasi kalah oleh sensasi.
Tak sedikit kasus menunjukkan ironi pahit: pelapor yang semula merasa “mencari keadilan” justru berakhir sebagai terlapor, karena unggahannya sendiri melanggar hukum.
Negara Hukum Tidak Boleh Tumbang oleh Linimasa
Jika setiap konflik diselesaikan lewat unggahan, maka institusi hukum kehilangan wibawanya. Polisi, jaksa, dan pengadilan dikesampingkan oleh linimasa.
Ini bukan kontrol sosial. Ini pembangkangan terhadap sistem hukum. Negara hukum tidak boleh tunduk pada algoritma. Keadilan tidak ditentukan oleh jumlah like, share, atau komentar.
Saatnya Menarik Rem Digital
Media sosial bukan ruang bebas nilai. Ia menuntut tanggung jawab moral, etika, dan hukum. Menyebarkan tuduhan bukan solusi. Menghancurkan reputasi bukan jalan pintas menuju keadilan.
Jika praktik pengadilan jalanan digital terus dibiarkan, maka yang kita bangun bukan masyarakat kritis, melainkan masyarakat yang gemar menghukum tanpa berpikir.
Dan pada akhirnya, semua bisa menjadi korban. Termasuk mereka yang hari ini merasa paling benar.
Oleh: Tim Redaksi